PENDIDIKAN KHUSUS (DIKSUS) PENGAMBILAN SLAYER CONTRAS BONE
LAPORAN PENDIDIKAN KHUSUS (DIKSUS)
DEVISI MOUNTENEERING
Laporan DIKSUS ini diajukan untuk
memenuhi salah satu syarat untuk menjadi Anggota Penuh CONTRAS BONE
Di susun oleh :
NADIA
REGITA CAHYANI (TERI)
NRAC.217.06.052
CONTRAS BONE PERIODE
2021
KATA PENGANTAR
Segala
puji bagi Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat serta hidayahnya yang
karenanya penulis diberikan kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan laporan
Pendidikan Khusus (DIKSUS) Shalawat
serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah
menyampaikan petunjuk Allah SWT untuk kita semua sebagai petunjuk yang benar
dalam syariat Agama Islam.
Laporan
kegiatan Pendidikan Khusus (DIKSUS) ini
disusun sebagai hasil dari kegiatan pada Tanggal 24 - 27 September 2021. Adapun
tujuan dari kegiatan ini adalah salah satu persyaratan dari Contras Bone untuk
menjadi Anggota Penuh .
Penulis
sungguh sadar bahwa laporan kegiatan DIKSUS ini dapat selesai berkat dari
bantuan serta dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, peserta meminta
masukan dan kritikan yang dapat membangun penulis, yang kemudian dapat
menyempurnakan laporan ini.
Demikain
pengantar ini semoga dalam penulisan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi
siapa saja yang membacanya. Aminnn.
Watampone,
30 September 2021
Penyusun
NADIA REGITA CAHYANI
NRAC.217.06.052
KODE ETIK PENCINTA ALAM
1.
PENCINTA ALAM INDONESIA SADAR BAHWA ALAM BESERTA ISINYA
ADALAH CIPTAAN TUHAN YANG MAHA ESA.
2.
PENCINTA ALAM INDONESIA
SEBAGAI BAGIAN DARI MASYARAKAT INDONESIA SADAR AKAN TANGGUNG JAWAB KEPADA
TUHAN, BANGSA DAN TANAH AIR.
3.
PENCINTA ALAM INDONESIA
SADAR BAHWA PENCINTA ALAM ADALAH SEBAGAI MAKHLUK YANG MENCINTAI ALAM SEBAGAI
ANUGERAH TUHAN YANG MAHA ESA.
Sesuai dengan hakekat
diatas peserta dengan kesadaran menyatakan :
1.
Mengabdi kepada Tuhan
Yang Maha Esa.
2.
Memelihara alam beserta
isinya serta menggunakan sumber alam sesuai dengan kebutuhannya.
3.
Mengabdi kepada Bangsa
dan Tanah Air.
4.
Menghormati tata
kehidupan yang berlaku pada masyarakat sekitar serta menghargai manusia dan
kerabatnya.
5.
Berusaha mempererat
tali persaudaraan antara Pencinta alam sesuai dengan azas Pencinta alam.
6.
Berusaha saling
membantu serta menghargai dalam pelaksanaan pengabdian terhadap Tuhan, Bangsa
dan Tanah Air.
7.
Selesai
DAFTAR ISI
Halaman
B.
Rumusan
Masalah....................................................................................
1
B. Perlengkapan yang Digunakan13
C. Rincian Anggaran yang Digunakan13
B. Saran13
DAFTAR
PUSTAKA...........................................................................................
LAMPIRAN13
DAFTAR ISI
Halaman
II NAVIGASI DARAT4
III PETA13
V KOMPAS13
C. Cara Menggunakan Kompas....................................................................
B. Waktu yang Akan Dipergunakan13
C. Tanda-Tanda Medan................................................................................
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Perlengkapan yang Digunakan.........................................................14
Tabel 1.2 Rincian Anggaran yang
Digunakan...................................................15
Tabel 1.3 Peralatan yang
Digunakan................................................................16
Tabel 2.1 Personil
Kegiatan..............................................................................18
Tabel 2.2 Pelaksanaan
Kegiatan........................................................................19
Tabel 2.3.Rute Perjalanan .................................................................................19
Tabel 2.4 Survival .............................................................................................22
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Pencinta Alam adalah seseorang yang mencintai alam dan
semesta beserta isinya. Jadi Pencinta Alam
artinya sangat luas sekali, mencintai Hutan, Gunung, Laut, Bumi, Bulan,
Matahari dan sebagainya. Termasuk juga mencintai Manusia, mencintai diri
sendiri, bahkan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menciptakan alam
semesta beserta isinya, jadi pada hakekatnya Pencinta Alam itu sangat luas
artinya.
Kegiatan Mountaineering adalah salah satu olahraga favorit bagi Pencinta Alam
atau penggiat alam bebas, sebuah olahraga yang membutuhkan stamina Fisik,
Mental, Kesehatan dan Strategi untuk menjaga keselamatan dalam pendakian,
karena di setiap perjalanan tidak selalu menemukan perjalanan yang mulus dan
lancar. Dikarenakan medan dilalui banyak
terdapat rintangan dan tantangan sangat Ekstrim
dan membahayakan bagi keselamatan para pendaki,
namun hal tersebut tidak menggoyahkan semangat para pendaki. Tujuan
seseorang untuk melalukan pendakian semakin hari semakin berkembang baik
individu maupun kelompok, seperti perpetualangan Adventure dan hobby, segi ilmu pengetahuan, segi rekreasi dan
wisata wahana alam. Perkembangan ini dilakukan secara luas mencakup satu segi
saja atau berkaitan, misalnya berpetualang melakukan pendakian saja atau untuk
olahraga sekaligus rekreasi dan wisata.
Kegiatan Pendidikan Khusus (DIKSUS) menjadi
salah satu persyaratan untuk menjadi Anggota Penuh dari Organisasi Contras Bone
dan merupakan sarana menjalankan Organisasi petualang, baik untuk menjaring
minat anggota maupun sebagai alat bertukar pikiran nilai-nilai kepencintaalaman.
Pencinta Alam bahkan bisa dikatakan bukan Pencinta Alam jika tidak terdapat
kegitan Outdoor di dalamnya. Hal tersebut
karena sejarah panjang Pencinta Alam yang kemudian telah membuat citra yang
begitu melekat pada penulis bahwa Pencinta Alam adalah Organisasi berbasis
petualangan. Dibalik kegiatan Outdoor terselip
nilai-nilai yang ditanamkan seperti lebih peduli dengan alam dan sekitarnya,
lebih menghayati dan lain sebagainya.
Pada kegiatan alam ini, Pencinta Alam
sangat menekankan pada pengetahuan mereka dalam berkegiatan di alam terutama
bagaimana melihat resiko dari aktivitas mereka. Para Anggota Contras Bonepada
akhirnya akan dituntut mempunyai persiapan yang matang ketika hendak mengadakan
kegiatan di alam. Hal ini sangat utama dan penting bagi mereka. Mereka sering
menyebut ini dengan manajemen kegiatan. Manajemen kegiatan tersebut disusun
hingga sangat detail, bahkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang sifatnya
pendidikan diwajibkan untuk mempresentasikan kesiapan mereka.
B.
Rumusan Masalah
Adapun Rumusan
Masalah dari Pendidikan Khusus (DIKSUS)
CONTRAS BONE adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana anggota
mengaplikasikan materi kePencintaalaman pada saat dialam bebas?
2. Bagaimana pola
pemahaman dan komunikasi yang terjadi antara anggota pada saat di alam bebas?
3. Bagaimana anggota
bertahan hidup dialam bebas?
C.
Tujuan
Adapun tujuan dari Pendidikan Khusus
(DIKSUS) CONTRAS BONE adalah sebagai berikut:
1.
Sebagai salah satu syarat/tahap untuk
menjadi Anggota Penuhseperti yang dijelaskan dalam AD/ART Contras Bone.
2.
Menambah pengalaman di bidang petualangan,
kepencintaalaman dan lingkungan.
3.
Mengaplikasikan materi yang diperoleh dari
Pendidikan Dasar atau Training Anggota Muda (TAMA).
4.
Sebagai referensi yang dapat di gunakan
para anggota yang ingin melakukan pendakian.
BAB II
GAMBARAN UMUM
LOKASI
A.
Gambaran umum
lokasi
Dalam kegiatan Pendidikan Khusus (DIKSUS) Mountaineering atau Pendakian Gunung
dilaksanakan di Ningo sampai Ajapanisi, dengan waktu yang dapat di tempuh
selama 3 malam 3 hari dari kota Watampone ke Ajapanisi. Dan dilokasi Camp pertama yaitu di Ningo dengan titik
505o dengan suasana yang sejuk dan pemandangan yang indah .
Dari lokasiCamp pertama yaitu Ningo, terdapat
banyak Tumbuhan dan Pepohonan yang tumbuh, dan jalur yang begitu
beragam. Landai, Terjal, Curam. Dan kondisi sumber air pada lokasi tersebut ada
yang dekat dan ada yang jauh. Adapun beberapa Flora dan Fauna yang ada di sekitar lokasi tersebut seperti :
1.
Flora (Tumbuhan) :
a.
Pohon Jagung
b.
Pohon Pisang
c.
Pohon Cengkeh
d.
Pohon Coklat
e.
Pohon Bambu
f.
Pohon Jambu
g.
Pohon Tomat
2.
Fauna (Hewan) :
a.
Sapi
b.
Anjing
c.
Kupu-Kupu
d.
Elang
e.
Kunang-Kunang
f.
Semut
B.
Kegiatan Diksus (Mounteneering)
Pada kegiatan Pendidikan Khusus (DIKSUS) Pendakian
Gunung (Mounteneering) tahap awal
persiapan untuk melakukan perjalanan terlebih dahulu peserta Pendidikan Khusus
(DiKSUS) wajib menerima arahan oleh pendamping agar selama kegiatan tidak
menyalahi aturan-aturan seperti di jelaskan oleh pendamping bahwa etika
perjalanan atau pendakian tidak boleh meninggalkan kecuali jejak, tidak
mengambil sesuatu kecuali gambar.
Tahap selanjutnya yaitu para peserta Pendidikan
Khusus (DIKSUS) melakukan perjalanan sesuai aturan atau tahap yang harus mereka
lalui untuk sampai ke titik yang sudah ditentukan oleh pendamping Pendidikan
Khusus (DIKSUS), sebelumnya mengecek alat Navigasi yang akan digunakan.
Memasuki tahap penentuan titik koordinat,
pada dasarnya penentuan titik koordinat atau yang biasa kita sebut Navigasi,
tiap masing-masing peserta mencari titik koordinat atau lokasi yang akan kita
lewati dan menghitung berapa waktu jarak tempuh untuk sampai dari titik satu ke
titik kedua, dan kegiatan berlangsung selama 3 malam 3 harihingga mencapai
titik terakhir.
BAB III
KRONOLOGI KEGIATAN
A.
Waktu Kegiatan
Dalam kegiatan Pendidikan Khusus (DIKSUS) dilaksanakan selama 3 hari untuk
menerapkan materi selamaTraining Anggota Muda (TAMA) serta menjadi salah satu syarat untuk menjadi
bagian Anggota Penuh Contras Bone. Adapun
materi yang di terapkan selama kegiatan Pendidikan Khusus (DIKSUS) yaitu Manajemen Perjalanan, Rock Clambing, Navigasi
Darat, Survival, Observasi lingkungan sekitar, dan Sosialisasi
Pedesaan (SOSPED).
Waktu kegiatan dilaksanakan pada Tanggal,
24 - 27 September 2021. Untuk melakukan perjalanan terlebih dahulu peserta
wajib menerima arahan oleh Instruktur atau
pendamping pada pukul 20.29 Wita agar selama proses kegiatan tidak menyalahi
aturan dalam etik perjalanan. Adapun
arahan yang diberikan oleh pendamping yaitu untuk menerapkan manajamen
perjalanan, serta mematuhi segala aturan kode etik pencinta alam selama
perjalanan agar sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi. Dalam hal untuk
mengantisipasi masalah dalam perjalanan seperti kehilangan arah, maka peserta
dan pendampingharus mampu bertahan hidup di alam bebas dengan cara menerapkan
materi Survival, Sosialisasi Pedesaan
(SOSPED) dan Navigasi.
Adapun kronologi selama kegiatan Pendidikan
Khusus (DIKSUS) berlangsung sebagai
berikut :
1.
Pada
hari Jumat, manajemen untuk berangkat sekitaran jam 14.00 Wita, tapi karena ada
kendala dengan mobil jadi peserta beserta pendamping berangkat malam dari Sekretariat ke Puncak Ningo pada pukul
20.32 Wita, sampai di sekitaran Ningo peserta singgah di rumah pendudukmengambil
air, kemudian peserta sampai di lokasi Camp
pertamapada pukul 21.43 Wita, kemudian peserta langsung membersihkan sekitaran
lokasi Camp dan memasang flysheet sekitaran tempat Camp untuk menghindari angin,setelah
selesai peserta memasak persiapan makan
malam pada pukul 22.11 Wita setelah masakan matang, kemudian para
peserta dan pendamping makan malam pada pukul 22.58 Wita, setelah makan malam
selesai para peserta membersihkan alat masak yang sudah terpakai, setelah itu
peserta dan pendamping berdiskusi tentang kegiatan kita keesokan harinya sampai
berdiskusi lepas selama beberapa jam, setelah pembahasan selesai, peserta
siap-siap untuk istirahat pada pukul 00.39 Wita, keesokan harinya peserta bagun
pada pukul 05.28 Wita, peserta langsung membersihkan sekitaran beberapa menit,
kemudian memasak untuk sarapan pagi pada pukul 06.25 Wita, setelah menu sarapan
sudah matang, kemudian peserta makan pada pukul 07.30 Wita, setelah selesai
sarapan pagi,peserta membersihkan dan berdiskusi
lepas, sekaligus packing pada pukul 07.54 Wita, setelah packingan selesai, peserta
langsung kumpul dan Breefing sebelum berangkat, setelah itu peserta berangkat pada
pukul 08.13 Wita, selang beberapa menit peserta singgah di ketinggian 505o untuk melakukan Resection pada pukul 08.24 Wita. Peserta langsung mengeluarkan alat
Navigasi berupa Peta, Kompas Bidik, Kompas Silva, Penghapus, Pensil, Penggaris,
Busur Derajat, kemudian peserta cari lokasi yang datar dan meletakkan Peta dan
Kompas Silva untuk mengutarakan Peta, setelah peserta mengetahui arah utara,
peserta membidik kisaran Bulu Jeppu dengan sudut kompas 116odan Bulu
Manumanu dengan sudut kompas145o, kemudian peserta menarik garisdari
titik 505oke Bulu Jeppu dan Bulu Manumanu, kemudian perpotongan
garis tersebut disitulah posisi peserta pada peta, setelah mengetahui posisi
pada peta, peserta langsung tarik garis menggunakan busur derajat dari titik
505o ke Laule dengan titik 482o. Titik 505o ke
482o hasilnya 176o kemudian peserta mengambil Kompas
Silva dan mengunci kompas dengan 176o, setelah kunci kompas peserta
langsung jalan mengikuti arah Kompas tersebut, medan yang di lalui beragam ada
yang landai, curam bahkan terjal dan kiri kanan jalur jurang, peserta terus
berjalan mengikuti arah kompas dan mencari medan yang mudah untuk di lalui dan
tidak menguras tenaga, setelah beberapa menit jalan,peserta singgah untuk
beristirahat beberapa menit pada pukul 09.30 Wita, setelah itu peserta
melanjutkan perjalanan pada pukul 09.35
Wita, peserta terus berjalan dan sekali-kali melihat kompas dan peta untuk
memastikan bahwa peserta tidak salah arah, kemudian peserta menemukan sumber
air dan peserta singgah mengambil air pada pukul 10.10 Wita, karena para
peserta dan pendamping kehausan, setelah itu peserta lanjut perjalanan pukul
10.15 Wita beberapa menit dan melihat flora dan fauna sekitaran jalur, kemudian
peserta menemukan sungai besar peserta memutuskan untuk istirahat sejenak dan peserta
mengeluarkan peta untuk memastikan bahwa arah peserta sudah benar dengan
melihat sekitaran sungai dan medan yang ada pada peta, setelah observasi di sungai peserta menemukan
posisi pada peta tanpa Resection hanya
membaca medan sebenarnya dan medan pada peta, setelah itu peserta mengatur
jalur yang ingin dilalui dengan melihat garis kontur pada peta, dan kemudian peserta
memutuskan mengambil arah yang landai tanpa menerobos garis kontur, setelah
beberapa menit istirahat, peserta melanjutkan perjalanan pada pukul 12.30 Wita peserta
berjalan dengan memperhatikan sekitaran jalur dan medan pada peta, penulis
bertugas melihat medan pada peta, Cupang bertugas sebagai Navigator dan
Baronang bertugas melihat arah kompas menuju ke arah yang akan dilalui, parapeserta
membagi tugas untuk memudahkan pada saat berjalan, kemudian singgah beristirahat
pada pukul 12.59 Wita, setelah beberapa
menit istirahat kemudian melanjutkan perjalanan pada pukul 13.02 Wita dan
menemukan Rumah penduduk di Desa Cenregading kemudianpeserta melakukan
Sosialisasi Pedesaan (SOSPED), kemudian melanjutkan perjalanan pada pukul 13.48
Wita, jalur yang sangat terjal di lalui dengan susur sungai dan air terjun,
dengan cuaca buruk sehingga peserta singgah memasang jas hujan,setelah berjalan
terus menerus dan akhirnya sampai di pertigaan Laule pukul 18.00 Wita, dan peserta pergi di suatu
rumah untuk memastikan bahwa betul ini lokasi tujuan di Laule, setelah
mendapatkan informasi, peserta mencari penjual untuk ngemil, dan berbincang
karena kebetulan penjualnya orang Bone Kota, maka dari itu pembahasan jadi
panjang dan peserta di suruh melapor ke Rumah Pak Dusun dan diarahkan ke
Rumahnya, dan peserta siap-siap berjalan menghampiri Rumah Pak Dusun, Kampung
Laule adalah kampung yang berpenduduk sedikit, Rumah penduduk tidak sampai 30
Rumah, jaringan tidak ada bahkan listrikpun tidak ada, setelah peserta mendapatkan Rumah Pak Dusunpesertaisin
dan di suruh nginap di Rumahnya karena waktu yang tidak memungkinkan untuk
mencari lokasi Camp, jadi para
peserta dan pendamping memutuskan nginap di Rumah Pak Dusun, kemudian peserta
mandi pada pukul 18.47 Wita, setelah mandi, penulis memasak untuk makan malam
pada pukul 19.27 Wita, setelah masakan sudah matangpeserta semua makan malam
pukul 20.35 Wita, setelah makan malam selesai, kemudian mencuci alat yang
digunakan untuk memasak, kemudian peserta kumpul dan evaluasi sekitaran 1 jam, peserta
tidak bisa berlama-lama karena lampu terbatas dan kemudian waktunya
beristirahat pada pukul 22.35 Wita.
2.
Pada
hari Minggu, penulis bangun pukul 07.12 Wita, penulis langsung ke kamar mandi,
kemudian peserta memasak untuk sarapan pagi pada pukul 07.35 Wita, setelah
beberapa menit, masakan sudah matang, dan kemudian sarapan pada pukul 08.18
Wita, setelah selesai sarapan, peserta mencuci alat yang digunakan, setelah itu
peserta packing pada pukul 09.26 Wita, setelah packingan selesai, kemudian peserta
foto bersama dengan Pak Dusun sekaligus pamit untuk melanjutkan perjalanan pada
pukul 09.40 Wita, kemudian kita ke pertigaan Laule untuk menarik busur dari
pertigaan Laule ke Bulu Manumanu dengan sudut kompas 96o, kemudian peserta
langsung kunci kompas dan berangkat pukul 10.11 Wita mengikuti arah kompas
tersebut, peserta berjalan terus-menerus selama beberapa menit, dan peserta
singgah istirahat sejenak pada pukul 11.05 Wita, setelah istirahat beberapa
menit peserta melanjutkan perjalanan pada pukul 11.14 Wita, medan yang dilalui
kebanyakan terjal, kemudian peserta menemukan air terjun bercabang dan
istirahat sejenak pada pukul 12.43 Wita, peserta kemudian observasi sungai untuk memastikan posisi kita pada peta, setelah observasipeserta menemukan posisi
sebenarnya maupun posisi pada peta, kemudian melanjutkan perjalanan pada pukul
13.05 Wita dengan memutuskan untuk susur sungai, beberapa jam kemudian peserta
menemukan air terjun dan istirahat sejenak pukul 14.34 Wita dan membuka peta
untuk membaca medan, tapi medan pada peta jalurnya begitu terjal dan peserta
memutuskan untuk tetap melanjutkan susur sungai pukul 14.45 Wita, setelah susur
sungai peserta kembali melewati hutan rimba dengan medan yang sangat terjal, peserta
tetap melanjutkan perjalanan, kompas peserta melenceng jauh karena mencari
medan yang mudah dengan melewati punggungan bukit, cuaca begitu buruk dan peserta
keburu waktu, dan kemudian singgah untuk
memasang jas hujan karena cuaca tidak mendukung, setelah berjalan kembali peserta
lintas air terjun dan susur sungai sampai menemukan medan yang mudah, dan peserta
mencari lokasi Camp karena waktu
sudah magrib dan kita belum sampai di Bulu Manumanu karena cuaca jelek, medan
tidak mendukung, maka dari itu peserta memutuskan Camp di Ladang pinggir sungai Boejeng pada pukul 17.23 Wita,
setelah sampai di lokasi Camp ke 3 pesertabersih-bersih
pada pukul 17.26 Wita, setelah itu kemudian peserta mendirikan Bivak pada
pukul 17.30 Wita, setelah Bivak jadi peserta
memasak untuk makan malam pada pukul 18.10 Wita, setelah makanan sudah matang,
kemudian peserta makan malam pukul 19.30 Wita, setelah makan malam, peserta
berkumpul dan evaluasi pukul 20.35 Wita, peserta mencari posisi pada saat di
lokasi Camp ke 3 pada peta, setelah peserta
menemukan posisi di peta kemudian langsung
mengatur jalur yang mau dilalui keesokan harinya, setelah evaluasi,peserta
istirahat pada pukul 23.43 Wita.
3.
Hari
Senin, penulis bangun pukul 06.48 Wita, kemudian penulis langsung membersihkan
selama beberapa menit, setelah beberapa menit kemudian, peserta bikin kopi
pukul 06.58 Wita, peserta hanya ngopi karena Ransum peserta sudah habis,
setelah itu peserta packing 07.45 Wita, setelah packingan selesai peserta tarik
busur dari sungai Boejeng ke pertigaan Ajapanisi dengan sudut kompas 70o,
setelah itu peserta langsung kunci kompas dan langsung berangkat pukul 08.35
Wita, peserta mengikuti arah kompas dan peserta memutuskan susur sungai karena
medan pada peta terjal, maka dari itu peserta mencari jalur yang mudah, setelah
berjalan beberapa jam peserta singgah pukul 09.40 Wita untuk istirahat, setelah
itupeserta tarik busur dari tempat persinggahan ke pertigaan Ajapanisi dengan
sudut kompas 140o, kemudian kunci kompas dan melanjutkan perjalanan
pada pukul 13.56 Wita, selang beberapa jam berjalan, kemudian peserta sampai di
pertigaan Ajapanisi pukul 15.15 Wita dan disitulah titik finish peserta, dan
kemudian peserta di jemput untuk pulang ke Sekretariat
dan peserta sampai di Sekretariat
pada pukul 16.45 Wita.
B.
Tabel Pralatan
dan Perlengkapan
Berikut merupakan daftar tabel peralatan dan perlengkapan
yang digunakan pada saat pelaksanaan Pendidikan Khusus ( DIKSUS ).
Tabel 1.1 Perlengkapan yang digunakan pada
saat DIKSUS
|
NO |
NAMA |
JUMLAH |
KETERANGAN |
|
1 |
DRY
BAG |
1 |
BAIK |
|
2 |
FLYSHEET |
2 |
BAIK |
|
3 |
TABUNG |
5 |
BAIK |
|
4 |
PARANG |
3 |
BAIK |
|
5 |
COOKING
SET |
1 |
BAIK |
|
6 |
CARRIER |
2 |
BAIK |
|
7 |
PORTEBEL |
2 |
BAIK |
|
8 |
WEBBING |
1 |
BAIK |
|
9 |
TALI
PRAMUKA |
3 |
BAIK |
|
10 |
HETLEM |
1 |
BAIK |
|
11 |
MATRAS |
5 |
BAIK |
|
12 |
NESTING |
1 |
BAIK |
|
13 |
SENDOK |
3 |
BAIK |
|
14 |
PIRING |
4 |
BAIK |
|
15 |
PISAU |
1 |
BAIK |
|
16 |
BENANG |
1 |
BAIK |
|
17 |
GELAS |
5 |
BAIK |
|
18 |
SENDOK
NASI |
1 |
BAIK |
|
19 |
PETA |
2 |
Hilang satu |
|
20 |
BUSUR
DERAJAT |
3 |
BAIK |
|
21 |
PENSIL |
1 |
BAIK |
|
22 |
PENGHAPUS |
1 |
BAIK |
|
23 |
PENGGARIS |
1 |
BAIK |
|
24 |
KOMPAS
SILVA |
3 |
BAIK |
|
25 |
KOMPAS
BIDIK |
2 |
BAIK |
C.
Rincian Anggaran
yang Digunakan
Berikut
merupakan daftar tabel rincian anggaran yang digunakan pada saat pelaksanaan
Pendidikan Khusus ( DIKSUS ).
Tabel 1.2 Rincian
Anggaran LOGISTIK
|
NO |
NAMA |
JUMLAH |
HARGA |
|
1 |
MIE EKO |
2
BUNGKUS |
Rp. 14.000 |
|
2 |
KOPI |
1
BUNGKUS |
Rp.
19.000 |
|
3 |
SUSU |
1
REFIIL |
Rp. 15.000 |
|
4 |
TISSUE |
1
BUNGKUS |
Rp.
7.500 |
|
5 |
MINYAK |
1
REFIIL |
Rp.
7.500 |
|
6 |
BERAS |
3
LITER |
SUMBANGSI |
|
7 |
NUTRISARI |
2
GANTUNG |
Rp. 21.000 |
|
8 |
LOMBOK BOTOL |
1
BOTOL |
Rp.
4.500 |
|
9 |
KECAP BOTOL |
1
BOTOL |
Rp.
4.500 |
|
10 |
IKAN KERING |
5
EKOR |
Rp.
10.000 |
|
11 |
TELUR |
11
BUTIR |
SUMBANGSI |
|
12 |
LOMBOK BIJI |
- |
SUMBANGSI |
|
13 |
BAWANG MERAH |
- |
Rp.
2.500 |
|
14 |
BAWANG PUTIH |
- |
Rp.
2.500 |
|
15 |
ASAM |
- |
Rp.
5000 |
|
16 |
SUNGLIGHT |
1
SUSET |
Rp.
2000 |
|
17 |
MASAKO |
1
GANTUNG |
Rp.
5000 |
|
18 |
POLY BAG |
1
PAK |
Rp.
25.000 |
|
19 |
BUSUR |
2 |
Rp.
8000 |
|
20 |
PENSIL |
1 |
Rp.
2000 |
|
21 |
PENGGARIS |
1 |
Rp.
3000 |
|
22 |
PENGHAPUS |
1 |
Rp.
1000 |
|
23 |
KOMPAS SILVA |
1 |
Rp.
50.000 |
|
24 |
ROMA KELAPA |
1
BUNGKUS |
Rp.
8000 |
|
25 |
BISKUIT PIRAMIT |
2
BUNGKUS |
Rp.
7000 |
|
26 |
ROTI TAWAR |
2
BUNGKUS |
Rp.
18.000 |
|
27 |
KUE PIA |
1
BUNGKUS |
Rp.
5000 |
|
28 |
PITSIN |
1
BUNGKUS |
Rp.
5000 |
|
29 |
GARAM |
1
BUNGKUS |
Rp.
1000 |
|
30 |
GULA |
1/2
LITER |
Rp.
11.000 |
|
31 |
TERIGU |
- |
SUMBANGSI |
|
32 |
TOMAT |
- |
SUMBANGSI |
|
33 |
KOL |
- |
SUMBANGSI |
|
34 |
TEMPE |
1
BUNGKUS |
SUMBANGSI |
|
Jumlah |
Rp. 264.000 |
||
D.
Kendala
1.
Manajemen waktu tidak sesuai dengan apa
yang direncanakan dan tidak kesesuaian apa yang telah di sepakati karena mobil
datang dari Pelabuhan Bajoe sehingga mengakibatkan keterlambatan berangkat ke
lokasi.
2.
Ransum kurang karena modal berkecukupan.
3.
Kurang memahami cara pembacaan medan
disebabkan peserta keliru dengan medan pada peta tidak sesuai dengan medan sebenarnya.
4.
Tidak melakukan olahraga sebelum turun
lapangan disebabkan jadwal kegiatan lain yang padat jadi tidak menyempatkan
olahraga sebelum turun ke lokasi.
5.
Satu peta hilang di bawa arus sungai karena
peserta menyusur sungai dengan cuaca hujan dan arus air sangat deras sehingga
Cupang terjatuh dan tidak sempat menyelamatkan peta, karena peta berada di
carrier Cupang.
BAB IV
PEMBAHASAN
A.
Persiapan
Perjalanan
Persiapan terhitung mulai pendalaman materi
yang diaplikasikan pada saat di lokasi, setelah itu para pendamping membuat
plog jalur yang akan di lalui untuk pendidikan, setelah membuat jalur kemudian
pendamping mengarahkan peserta untuk praktek mengaplikasikan materi navigasi
sebelum pengaplikasian di alam bebas, keesokan hari nya peserta membeli ransum
dan mempersiapkan alat yang digunakan pada saat Pendidikan Khusus (
DiKSUS ).
Persiapan manajemen perjalanan terhitung
mulai Tanggal 24 - 27 September 2021. Yang dimulai dari Puncak Ningo sampai
pertigaan Ajapanisi. Dari lokasi Camp
pertama yaitu Puncak Ningo,
beberapa lokasi atau perbukitan yang sudah ditargetkan untuk sampai di
pertigaan Ajapanisi. Dari lokasi tersebut terdapat banyak flora dan fauna.
B.
Personil Pendakian
Tabel 2.1 Tim yang
melakukan Pendidikan Khusus.
|
NO |
NAMA |
TELEPON |
ALAMAT |
KETERANGAN |
|
1 |
Syarman Yudi |
081918159041 |
Btn Pepabri Blok B2 No. 13 |
Pendamping Diksus |
|
2 |
Awaluddin |
082281443833 |
Btn Pepabri Blok B2 No. 13 |
Pendamping Diksus |
|
3 |
Muh. Idris |
082154026853 |
Btn Pepabri Blok B2 No. 13 |
Pendamping Diksus |
|
4 |
Nadia Regita Cahyani |
085340739886 |
Btn Pepabri Blok B2 No. 13 |
Peserta Diksus |
|
5 |
Haikal |
085339455448 |
Btn Pepabri Blok B2 No. 13 |
Peserta Diksus |
|
6 |
Muh. Hanif Buhasyim |
085796408053 |
Btn Pepabri Blok B2 No. 13 |
Peserta Diksus |
C.
Pelaksanaan
Kegiatan
Cara menentukan BackAzimuth :
1.
Titik awal dan titik akhir perjalanan di
plotkan pada peta, kemudian tariklah garis lurus dan hitung sudut kompas yang
menjadi arah perjalanan. Hitung juga sudut dari titik akhir ke titik awal,
kebalikan arah perjalanan. Sudut kebalikan arah perjalanan ini adalah
sudut BackAzimuth.
2.
Perhatikan suatu objek yang menyolok (misalnya
pohon besar, pohon tumbang, longsoran
tebing, susunan pohon yang khas, ujung kampung dan sebagainya) pada titik awal
perjalanan.
3.
Bidikan kompas sesuai dengan arah perjalanan
kita (sudut kompas), dan tandai dengan salah satu objek yang berada dijalur
lintasan yang akan dilalui pada arah itu.
4.
Setelah
anda sampai pada objek itu, bidiklah kompas kebelakang (BackAzimuth)
untuk memeriksa kembali apakah anda berada pada lintasan yang tepat.
Bergeserlah ke kiri atau ke kanan untuk mendapatkan BackAzimuth yang
benar.
5.
Sering kali tidak ada objek yang dapat
dijadikan sasaran. Dalam hal ini pakailah teman kita sebagai titik objek
sementara dan dilakukan secara beranting. Lebih baik perjalanan lambat asal
tidak tersesat.
Keterangan
:
SK
– AB : Sudut kompas perjalanan dari A ke B, SK – BC : Sudut kompas dari C ke B
(BackAzimuth dari C ke B), SK – BA : Sudut kompas dari B ke A (BackAzimuth dari
B ke A)
Cara mencari sudut
balik kompas atau sudut BackAzimuth:
1.
Bila sudut kompas sasaran kurang dari 1800,
maka BackAzimuthnya adalah: sudut kompas ditambah dengan 1800.
Contoh : Sudut kompas 450. Maka BackAzimuthnya adalah:
450+1800=2250.
2.
Bila sudut kompas sasaran lebih dari 1800,
maka BackAzimuthnya adalah : sudut kompas dikurangi dengan 1800.
Contoh : Sudut kompas sasaran lebih dari 2200. Maka BackAzimuthnya :
2200–1800=400.
a.
Rumus
mencari sudut BackAzimuth:
Jika X0 < 1800 =
X0 + 1800
Jika X0 > 1800 =
X0 - 1800
b.
Rumus mencari detik :
Jarak = 60 (detik)
3,7 (ukuran karvak)
Contoh :
2,5 cm = 60= 40,5 detik
3,7
Tabel 2.2 Pelaksanaan
kegiatan
|
NO |
RUTE |
WAKTU TEMPUH |
KETERANGAN |
|
1 |
Puncak Ningo – Laule |
± 10 jam |
Pendakian dan susur sungai |
|
2 |
Laule – Salo Boejeng |
± 8 jam |
Pendakian, susur sungai, dan air terjun |
|
3 |
Salo Boejeng - Ajapanisi |
± 2 jam |
Pendakian, susur sungai, landai |
1.
Rute Perjalanan
Tabel 2.3 Rute perjalanan
|
NO |
LOKASI |
KETINGGIAN |
KOORDINAT |
SUDUT KOMPAS |
KET |
|
1 |
Puncak Ningo |
505oMDPL |
LS. 04o,32’,40,5” BT. 120 o,07’,27,5” |
A. 171 o B. 351 o |
Sudut kompas dari puncak Ningo ke
Pertigaan Laule |
|
2 |
Persinggahan |
400oMDPL |
LS. 04o,33’,26,5” BT. 120 o,04’,29,1” |
A. 150 o B. 330 o |
Salo Cenregading |
|
3 |
Persinggahan |
350oMDPL |
LS. 04o,34’,27,5” BT. 120 o,07’,37,2” |
A. 117 o B. 297 o |
Salo Bajoeng |
|
4 |
Camp 2 |
400o
MDPL |
LS. 04o,’35,6,48” BT. 120 o,07’,17,8” |
A. 96 o B. 276 o |
Rumah Pak Dusun |
|
5 |
Pertigaan Laule |
350oMDPL |
LS. 04o,34’,42,1” BT. 120 o,08’,34” |
A. 87 o B. 267 o |
Sudut kompas dari pertigaan Laule ke Bulu
Manumanu |
|
6 |
Camp 3 Salo Bajoeng |
433oMDPL |
LS. 04o,35’,42,1” BT. 120 o,08’,34” |
A. 70 o B. 250 o |
Sudut kompas dari Salo Bajoeng ke
Pertigaan Ajapanisi |
|
7 |
Persinggahan |
400oMDPL |
LS. 04o,34’,25,9” BT. 120 o,09’,43,5” |
A. 55 o B. 235 o |
Rumah senior Budi |
|
8 |
Pertigaan Ajapanisi |
400oMDPL |
LS. 04o,34’,27,5” BT. 120 o,09’,30” |
A. 140 o B. 320 o |
Finish |
2.
Letak Geografis
Ningo Desa Timusu
a.
Luas Desa
dan Peruntukannya
Desa Timusu terletak
diwilayah Kecamatan Liliriaja yang dengan Luas Wilayah Desa Timusu adalah
1.500 Ha² meliputi Tanah Sawah, Tanah kering, Tanah Basah, Tanah Perkebunan dan
Tanah Hutan.
Batas Wilayah
1.
Sebelah
Utara :
Kelurahan JennaE
2.
Sebelah
Selatan : Desa Congko
3.
Sebelah
Barat : Desa
Rompegading
4.
Sebelah
Timur : Kelurahan
Labessi
b. Letak
Geografis
Secara geografis Desa Timusu terletak
diantara 4° 06° 00° – 4° 32° 00° Lintang Selatan dan 119° 42° 18° – 120° 06°
13° Bujur Timur, terletak sekitar 180 km disebelah utara Kota Makassar ibukota
Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Timusu memiliki temperature udara antara 24° –
30° C, keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang, dan curah hujan
rata-rata 175 mm dan 123 hari hujan pertahun. Geomorfologi Desa Timusu terdiri
dari daratan dan perbukitan, dimana sebagian besar wilayah Desa Timusu adalah
perbukitan selain itu terdapat sungai yang mengalir Sungai TengapadangE dan
Sungai LebbaE maka menjadi potensi sumber daya alam untuk mengairi tanah-tanah
pertanian dan perkebunan disekitarnya. Adapun potensi sumber daya alam lain
adalah mata air panas beccello dan goa Timusu dimana masih perlu mendapatkan
perhatian dari pemerintah untuk pemeliharaan dan pengembangannya.
c.
Keadaan
Iklim
Desa Timusu
beriklim tropis, suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, dengan rata-rata tidak
kurang dari 18° C, yaitu sekitar 27° C. Di daerah tropis, tidak ada perbedaan
yang jauh atau berarti antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim
kemarau.
Musim Hujan
terjadi pada bulan Oktober – April, pada saat itu petani mulai mengerjakan
lahannya untuk bercocok tanam. Jenis tanaman yang ditanam adalah tanaman yang
membutuhkan air pada awal pertumbuhannya, contohnya padi.
Musim Kering
terjadi pada bulan Mei – September, sebagian petani terpaksa membiarkan
lahannya tidak ditanami karena tidak ada pasokan air. Sebagian lainnya masih
dapat bercocok tanam dengan memanfaatkan air dari sungai, saluran irigasi atau
memanfaatkan sumber buatan. Ada pula petani yang berupaya bercocok tanam
walaupun tidak ada air yang cukup dengan memilih jenis tanaman atau varietas
yang tidak memerlukan banyak air.
d.
Topografi
Desa Timusu
terdiri dari daratan dan perbukitan, dimana sebagian besar wilayah Desa Timusu
adalah perbukitan selain itu terdapat sungai yang mengalir Sungai Tengapadange
dan Sungai Lebbae maka menjadi potensi sumber daya alam untuk mengairi
tanah-tanah pertanian dan perkebunan disekitarnya.
3.
Letak Geografis
Laule Desa Tellu Boccoe
Tellu Boccoe adalah
Desa di Kecamatan Ponre,Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, kode kemendagri
73.08.07.2005, luas 11,78 km2, jumlah penduduk 1.505 jiwa, kepadatan
12 jiwa/km2.
4.
Letak Geografis
Ajapanisi Desa Cinennung
Cinennung adalah
Desa di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, kode kemendagri
73.08.15.2001, jumlah penduduk 1.532 (2003).
3.
Survival
Tabel 2.4 Dalam
tabel ini dapat kita ketahui bahwa lokasi yang tertera di bawah dapat kita
terapkan materi survival.
|
NO |
LOKASI SURVIVAL |
KEGIATAN SURVIVAL |
KETERANGAN |
|
1 |
Desa Carigading |
Survival makanan |
Setelah menemukan rumah penduduk peserta survival makanan
yang ada disekitar seperti jambu |
|
2 |
Dusun Laule |
survival |
Sosped di rumah penduduk |
|
3 |
Camp 3 |
Mendirikan tenda flysheet |
Peserta mendirikan flysheet
pada Camp terakhir karena waktu
tidak cukup untuk mendirikan bivak alami |
BAB V
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Kegiatan Pendidikan Khusus (DIKSUS) ini dilaksanakan
di Puncak Ningo sampai Pertigaan Ajapanisi, kegiatan pendakian ini dilakukan
untuk pengambilan poin guna pengalihan dari Anggota Muda ke Anggota Penuh atau
pengambilan slayer pada Divisi Mounteneering.
B.
Saran
Laporan
ini adalah suatu bentuk data yang dapat
dipertanggungjawabkan dari data yang diperoleh pada saat praktik. Data
yang baik dan jelas merupakan salah satu kunci kesuksesan membuat laporan,
sehingga data yang diambil harus benar-benar dipahami agar mudah dalam
penyusunan laporan. Maka dari itu, penyusun menyarankan pada saat kegiatan praktik
harus mengetahui dan memahami metode pengambilan data yang baik, sehingga data
yang didapatkan lebih jelas dan dapat memberikan informasi lebih tepat sehingga
mudah dalam mengolah data.
DAFTAR
PUSTAKA
Haliman
dan Dian. 2007. Navigasi Darat
Nurdjana
. 1980. Letak geografis Timusu
Subaidah.S.,S.
Pramudjo Dan Manijo, 2009. Letak
geografis Tellu Boccoe..
Sutaman,1993. Letak geografis Cinennung. httP://zaldibiaksambas.files.wordpress.com/2010/10/Kepencintaalaman. pdf.
Wardaningsih,
1999. Pengertian Pencinta Alam. Universitas Terbuka Jakarta.
Lampiran 1. Foto kegiatan
Lampiran 2. Salo Carigading

Lampiran 3. Salo Bajoeng
Lampiran 4. Foto Bersama Pak
Dusun Laule
Lampiran 5. Evaluasi
Lampiran 6. Foto Bersama
Pendamping
Lampiran 8. Makan
Materi
NAVIGASI DARAT
I.
PENDAHULUAN
Sebagai orang yang
mengaku dekat dengan alam, pengetahuan peta dan kompas serta cara penggunaannya
adalah mutlak harus dimiliki. Perjalanan ke tempat-tempat yang jauh dan tidak
dikenal akan lebih dipermudah dengan memanfatkan keterampilan yang menggunakan
peta dan kompas. Pengetahuan navigasi darat ini juga berguna bila suatu saat
tenaga kita dibutuhkan untuk usaha-usaha pencarian dan penyelamatan korban
kecelakaan ataupun tersesat di gunung dan hutan, serta bencana alam. Dalam hal
ini, banyak bidang-bidang tertentu yang memerlukn pengetahuan navigasi.
II.
NAVIGASI DARAT
Navigasi darat adalah penentuan posisi dan arah perjalanan baik di medan
sebenarnya ataupun di peta. Istilah navigasi pada umumnya digunakan untuk
keperluan pelayaran dan penerbangan. Penambahan kata darat pada navigasi lebih
ditekankan pada penggunaan di daratan antara lain meliputi gunung, sungai,
lembah, rawa dan sebagainya.
Kunci untuk memahami
navigasi adalah:
a.
Mampu merekam dan membaca gambaran permukaan
pisik bumi.
b.
Mampu menggunakan peralatan pedoman arah.
Untuk memahami kedua
hal tersebut navigasi darat dibantu dengan peralatan peta dan kompas.
Keduanya digunakan bersamaan dan mempunyai fungsi yang saling menunjang.
Navigasi darat tidak usah dihapalkan akan tetapi lebih banyak dilatihkan untuk
dipraktekkan.
Navigasi laut adalah
visualisasi grafis ruang laut dan pantai yang menyajikan berbagai data yaitu
kedalaman laut (batrimetri), ketinggian daratan, morfologi (bentuk lahan) di
laut,garis pantai, bahaya navigasi, sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP),
instalasi buatan dipermukaan.
III.
PETA
Secara umum peta
adalah penggambaran dua dimensi (pada bidang datar) dari sebagian atau seluruh
permukaan bumi yang dilihat tegak lurus dari atas, dan diperkecil atau
diperbesar dengan perbandingan tertentu.
Peta tofografi pada
umumnya disertakan pula, yang akan membantu untuk mengetahui secara detail
daerah-daerah permukaan bumi yang terpetakan tersebut.
Keterangan-keterangan
tersebut antara lain :
a.
Judul peta
Judul peta mewakili
seluruh daerah yang terpetakan atau menyatakan lokasi yang ditunjukan oleh peta
yang bersangkutan. Umumnya dituliskan nama daerah yang paling menonjol. Lokasi
yang berbeda akan mempunyai judul yang berbeda. Judul peta ada pada bagian
tengah atas peta
b.
Keterangan pembuatan peta
Yaitu informasi dari
pembuatan peta tersebut, seperti tahun pembuatan, nama instansi yang membuat,
sistem proyeksi yang digunakan, untuk keperluan apa peta tersebut dibuat, dan
sebagainya. Contoh : peta yang dikeluarkan oleh Direktorat Geologi, Dinas
Tofografi Belanda, US Army Map Service, Bakosurtanal, dan sebagainya.
c.
Nomor peta
Yaitu menjelaskan
nomor registrasi peta. Dicantumkan di sisi kanan atas dengan dua cara
penulisan, yang mana angka latin untuk menyatakan nomor kolom dan angka romawi
untuk menyatakan nomor baris. Ex; 48/XL1-D
d.
Lembar derajat
Yaitu penjelasan
nomor-nomor peta lain yang tergambar di sekitar peta yang digunakan untuk
memudahkan kita jika ingin mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai suatu
daerah dengan menggabung-gabungkan bagian-bagian lain peta tersebut. Dalam lembar
derajat juga tercantum nomor-nomor peta yang ada disekeliling peta tersebut.
Lembar derajat berada di sisi kiri bawah.
e.
Koordinat peta
Koordinat adalah
kedudukan suatu titik pada peta, atau kedudukan titik pada suatu bidang
atau terhadap dua garis bilangan sistem koordinat pada peta. Sistem koordinat
ditentukan dengan menggunakan sistem garis sumbu yaitu garis-garis yang saling
berpotongan tegak lurus. Sistem koordinat yang resmi dipakai ada dua macam
yaitu :
1.
Koordinat geografis (geograficalcoordinate)
Sumbu yang
digunakan adalah garis bujur (bujur barat dan bujur timur) yang tegak
lurus terhadap garis khatulistiwa. Koordinat geografis dinyatakan dalam
derajat, menit dan detik.
2.
Koordinat Grid (gridcoordinate atau UTM)
Dalam koordinat grid,
kedudukan suatu titik dinyatakan dalam ukuran jarak terhadap suatu titik acuan.
Untuk wilayah Indonesia, titik acuan wilayah nol ini ada disebelah barat
Jakarta (600 LU, 980 BT). Garis vertikal diberi
nomor urut dari barat ketimur. Sistem koodinat mengenal penomoran dengan 4
angka atau 6 angka. Untuk daerah yang luas dipakai penomoran 4 angka, sedangkan
untuk daerah yang lebih sempit menggunakan penomoran 6 angka.
f.
Garis Kontur
Kontur adalah garis
khayal yang menghubungkan titik-titik berketinggian sama dari muka laut, berbelok-belok
mengikuti ketinggian yang sama dan tertutup. Garis kontur dimaksudkan untuk :
1.
Untuk mengetahui tinggi letak suatu tempat
dari permukaan laut.
2.
Untuk mengetahui bentuk dilapangan yang
sebenarnya. Oleh karena itu garis kontur ini dinamakan juga garis sama tinggi.
g.
Skala Peta
Skala peta adalah
perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak horizontalsebenarnya
dilapangan.
Skala peta
: Jarak di peta
Jarak dilapangan
Sifat skala :
1.
Makin kecil angka di belakang tanda bagi (:),
makin besar skala itu.
2.
Makin besar angka di belakang tanda bagi (:),
makin kecil skala itu.
Cara menyatakan skala :
1.
Dengan perkataan : Satu senti meter berbanding
setengah kilometer.
2.
Dengan pecahan : 1 : 50.000 atau 1/50.000,
berarti satu senti meter pada peta sama dengan 50.000 cm (500 m 0,5 km) pada
jarak sesungguhnya.
3.
Dengan skala garis atau gambar
:
Berarti tiap bagian
sepanjang blok garis pada peta tersebut mewakili jarak 1 km jarak horizontal di
medan sebenarnya atau jarak sesungguhnya.
h.
Legenda Peta
Yaitu informasi
tambahan untuk mempermudah interpretasi peta baik dari unsur-unsur yang
dibuat manusia maupun alam. Hanya berlaku pada legenda peta,
informasi-informasi tambahan tersebut tidak disajikan sesuai dengan skala peta.
Pada umumnya legenda peta disajikan dalam bentuk gambar beserta keterangan
tertulis, termasuk perbedaan warna-warna (untuk peta berwarna). Legenda peta
biasanya disertakan pada bagian bawah peta. Bagian legenda ini memuat
simbol-simbol yang dipakai peta. Yang penting diketahui adalah : titik triangulasi,
jalan setapak, jalan raya, sungai, Desa, dan pemukiman, dan sebagainya.
i.
Tahun Peta
Peta topografi juga
memuat keterangan tentang tahun pembuatan peta tersebut. Semakin baru tahun
pembuatannya, maka data yang disajikan semakin akuarat.
j.
Arah Peta
Yang perlu
diperhatikan adalah arah utara peta. Cara yang paling mudah ialah dengan
memperhatikan arah huruf-huruf tulisan tegak yang ada di peta. Pada bagian
bawah biasanyajuga penunjuk arah Utara peta, Utara sebenarnya, dan Utara
magnetik.
Utara sebenarnya
adalah arah yang menunjukkan Kutub Utara bumi. Utara magnetik adalah arah utara
yang menunjukkan Kutub Utara magnetik bumi. Kutub Utara magnetik bumi letaknya
tidak bertepatan dengan Kutub Utara bumi, kira-kira berada di sebelah Utara
Kanada, di Jazirah Boothia, karena pengaruh rotasi bumi letak kutub utara
magnetik bumi bergeser dari tahun ketahun.
Utara magnetik ini
adalah arah utara yang ditunjukkan oleh jarum magnetik kompas. Untuk keperluan
praktis, utara peta, utara sebenarnya dan utara magnetik dapat dianggap sama.
Untuk kepeluan-keperluan yang lebih menuntut ketelitian perlu mempertimbangkan
adanya ikhtilap peta, ikhtilap magnetik, ikhtilap peta magnetik dan variasi
magnetik.
1. Ikhtilap peta,
adalah beda sudut antara utara sebenrnya dengan utara tetap. Beda sudut ini
terjadi karena kerataan jarak pararel garis bujur peta bumi menjadi garis
koordinat vertikal pada peta.
2. Ikhtilap
magnetik, adalah beda sudut antara utara sebenarnya dengan utara magnetik.
3. Ikhtilappetamagnetik,
adalah beda sudut antara utara peta dengan utara magnetik bumi.
4. Variasi
magnetik bumi, adalah perubahan atau pergeseran letak kutub magnetik bumi
pertahun.
IV.
MEMBACA PETA
a.
sifat-sifat garis kontur
1.
Garis kontur dengan ketinggian yang lebih
rendah mengelilingi garis kontur yang lebih tinggi, kecuali bila disebut secara
khusus untuk hal-hal tertentu seperti kawah.
2.
Garis kontur tidak akan pernah berpotongan
3.
Beda ketinggian antara dua garis kontur adalah
tetap, walaupun kerapatan dua garis kontur tersebut berubah-ubah.
4.
Daerah datar mpunyai kontur yang
jarang-jarang, sedangkan daerah terjal atau curam mempunyai garis kontur yang
rapat.
5.
Garis kontur tidak akan pernah bercabang.
6.
Punggung gunung atau bukit terlihat di peta
sebagai rangkaian garis kontur yang berbentuk huruf “U” yang ujung
melengkungnya menjauhi puncak.
7.
Lembah terlihat di peta sebagai rangkaian garis
kontur yang berbentuk huruf“V” yang ujungnya tajam dan menjorok ke arah puncak Garis
kontur berbentuk kurva tertutup.
8.
Garis ketinggian pembantu, menyatakan
ketinggian antara (tengah-tengah) antara dua garis yang berurutan.
b.
Ketinggian Tempat
Untuk menentukan suatu
ketinggian pada peta, yaitu dengan cara melihat interval kontur pada peta dan
lalu hitung ketinggian tempat yang ingin diketahui. Memang ada perkiraan umum
yaitu : interval kontur = 1/200 skala peta. Tetapi perkiraan ini biasanya tidak
selalu benar. Beberapa peta topografi keluaran Direktorat Geologi Bandung
aslinya berskala 1 : 50.000 (interval kontur 25 m), tetapi kemudian diperbesar
menjadi berskala 25.000 dengan kontur interval yang tetap 25 m. Dalam misi SAR
gunung hutan misalnya, sering kali suatu diperbesar dengan cara di fotocopy
untuk ini interval kontur peta tersebut haruslah tetap dituliskan.
Sering peta yang dikeluarkan
oleh Bakorsutanal (1 : 50.000) membuat garis kontur tebal untuk setiap
kelipatan 250 m (kontur tebal untuk ketinggian 750, 1000, 1250 m dan
seterusnya) atau setiap selang sepuluh kontur.
Peta yang dikeluarkan
oleh AMS (Army Map Service) yang berskala 1 : 50.000, membuat garis
kontur tebal untuk setiap kelipatan 100 m. Misalnya : 100,200,300 m dan
seterusnya.
Peta yang dikeluarkan
oleh Direktorat Geologi Bandung tidak seragam ketentuan garis konturnya. Dari
informasi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan khusus
dan seragam untuk menentukan garis kontur tebal.
Bila ketinggian garis
kontur tidak dicantumkan, maka untuk mengetahui ketinggian suatu tempat
haruslah dihitung dengan cara sebagai berikut :
1.
Cari
dus titik yang berdekatan yang harga ketinggiannya
diketahui (tercantum).
2.
Hitung selisih ketinggian antara kedua titik
tersebut hitung berapa kontur yang terdapat diantara keduanya (jangan
menghitung garis kontur yang sama harganya bila kedua titik terpisah oleh
lembah).
3.
Dengan mengetahui selisih ketinggian dua
titik tersebut dan mengetahui juga jumlah kontur yang terdapat, dapat dihitung
berapa interval konturnya (harus merupakan bilangan bulat).
4.
Lihat kontur terdekat dengan salah satu titik
ketinggian. Bila kontur terdekat itu berada diatastitikmaka harga kontur itu
lebih besar dari titik ketinggian itu. Bila kontur berada dibawah maka harganya
lebih kecil. Hitung harga kontur terdekat itu yang harus merupakan kelipatan
dari harga interval kontur yang telah diketahui dari point (c).
Lakukanlah perhitungan
diatas sampai merasa yakin harga yang didapat untuk setiap kontur benar,
cantumkan harga beberapa kontur pada peta anda (kontur 1000, 1.250, 1,500 dan
seterusnya) agar mudah mengingatnya.
c.
Mengenal Tanda Medan
Disamping tanda
pengenal yang terdapat di legenda peta topografi, kita bisa menggunakan
bentuk-bentuk atau bentang alam yang menyolok di lapangan, dan mudah dikenali
di peta, yang akan kita sebut dengan: “tanda medan”. Beberapa tanda medan yang
dapat kita “baca” dari peta sebelum anda berangkat ke lokasi, tetapi kemudian
harus anda cari di lokasi.
Beberapa tanda medan
yang dapat diperhatikan:
1.
Puncak gunung atau bukit, punggung gunung,
lembah antara dua puncak, danbentuk-bentuk tonjolan lain yang menyolok.
2.
Lembah yang curam, sungai, pertemuan anak
sungai, kelokan sungai, tebing-tebing sungai.
3.
Belokan-belokan jalan, jembatan (perpotongan
antara sungai dengan jalan), ujung desa, persimpanga-persimpangan jalan.
4.
Bila berada di pantai, muara sungai dapat
menjadi tanda medan yang sangat jelas, begitu juga tanjung yang menjorok ke
laut, teluk-teluk yang menyolok, pulau-pulau kecil, delta, dsb.
5.
Pada daerah dataran atau rawa-rawa biasanya
sukar menentukan tonjolan permukaan bumi atau bukit-bukit yang dapat
dimanfaatkan sebagai tanda medan. Pergunakanlah belokan-belokan sungai,
muara-muara sungai kecil.
6.
Dalam penyusuran di sungai, kelokan tajam,
cabang sungai, tebing-tebing. delta. dsb, dapat dijadikan sebagai tanda.
Pengertian tanda medan
ini mutlak perlu dikuasai, sebab akan berguna sekali, dan akan digunakan pada
uraian selanjutnya mengenai penggunaan “teknik peta dan kompas”.
V.
KOMPAS
Kompas adalah perangkat navigasi disamping peta yang berfungsi
sebagai petunjuk arah kutub-kutub magnetik bumi. Penggunaan kompas pada bidang
mendatar, selalu menunjukkan arah utara-selatan. Tetapi perlu diingat bahwa
arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas tersebut adalah arah utara magnetik
bumi. Sedangkan arah utara bumi berbeda dengan arah utara magnetik bumi. Jadi
arah yang ditunjukkan oleh kompas bukanlah arah utara bumi yang sebenarnya,
juga arah utara kompas tidak sama dengan arah utara peta. Tetapi untuk
sementara kita anggap utara kompas sama dengan utara peta.
1.
Bagian-bagian Kompas
Pada umumnya
secara fisik kompas terdiri dari tiga bagian yaitu:
a.
Jarum magnetik, selalu menunjukkkna arah
utara-selatan pada posisi bagaimanapun, dengan syarat kompas tidak dipengaruhi
oleh medan magnet lainnya, benda-benda besi lainnya, dipergunakan dalam posisi
mendatar atau horizontal dan jarum magnetik tidak terhambat perputarannya.
b.
Skala penunjuk atau skala lingkaran mendatar,
berfungsi menunjukknanya pembagian derajat sistem mata angin.
c.
Badan kompas atau bagian penyangga, yaitu
tempat komponen-komponen lainnya dari kompas berada.
Secara sederhana
bagian-bagian kompas seperti terdapat digambar sebelah ini. Sedangkan dalam
kenyataannya dapat berkembang bentuknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya.
2.
Jenis-jenis Kompas
Banyak macam kompas
yang dapat dipakai dalam suatu perjalanan. Tetapi pada umumnya dipakai dua
jenis kompas yaitu kompas bidik (misalnya kompas prisma) dan kompas orientering
(misalnya kompas silva). Kompas bidik mudah untuk membidik, tetapi dalam
membaca di peta perlu dilengkapi dengan busur derajat dang penggaris
(segitiga). Kompas silva kurang akurat jika dipakai untuk membidik, tetapi
banyak membantu dalam pembacaan dan perhitungan di peta. Kompas yang baik
biasanya mempunyai kriteria, diantaranya sebagai berikut: skala ketelitian
derajat yang akurat, jarum penunjuk arah yang stabil (biasanya pada bagian
badan kompas terdapat cairan yang agak menahan pergerakan jarum kompas sehingga
penunjukkan arah lebih cepat dan tepat). Pada ujung jarum biasanya dilapisi
fosfor agar dapat terlihat dalam keadaan gelap
3.
Menggunakan Kompas
Pengertian dasar
tentang kompas sebagai alat merupakan langkah 1. Secara prinsip tidak ada
perbedaan pada setiap tipe kompas, kendati demikian masing-masing mempunyai
ciri-ciri tersendiri yang mesti dipelajari terlebih dahulu. Bagaimanapun delapan
titik arah mata angin utama dalam kompas yang merupakan pokok penting untuk
diketahui lebih dahulu.
Delapan arah mata
angin tersebut ialah: Utara, Timur, Selatan, Barat, Timur Laut, Tenggara, Barat
Daya, Barat Laut. Di samping itu pula masih terdapat beberapa arah mata angin
lainnya yang derajatnya lebih kecil dan berada di sela-sela arah mata angin
yang utama. Agar lebih jelasnya, dapat diperhatikan gambar arah mata angin di
samping ini. Kompas dipakai dengan posisi horizontal sesuai dengan arah garis
medan magnetik bumi. Dalam memakai kompas terlebih dahulu jauhkan benda-benda
yang terbuat dari logam yang sekiranya dapat mengganggu jarum kompas. Jika kita
melakukan perjalanan menurut arah kompas (menggunakan kompas prisma atau lensa)
disiang hari, maka tindakan yang akan kita lakukan secara berturut-turut:
a.
Buka kompas dan dirikan tutup kompas tegak
lurus.
b.
Angkat tutup prisma atau lensa ke atas lensa
kompas.
c.
Masukan ruas 1 ibu jari tangan kanan atau kiri
ke dalam cincin ibu jari dan letakkan jari telunjuk menekan badan kompas atau
memegangi badan kompas.
d.
Bawa prisma atau lensa itu kemuka mata dan
lihatlah ke dalam celah bidik.
e.
Putar badan atau bidik sampai mendapat arah
yang ditentukan.
f.
Arah bidik dinyatakan oleh angka-angka yang
ditunjukkan oleh garis-garis prisma atau lensa dan garis rambut.
g.
Sambil melihat melalui garis carilah suatu
titik dan tanda-tanda di medan yang searah
h.
Pergilah ke titik yang dipilih, bila
telah sampai dititik tanda yang 1, carilah titik tanda kedua pada arah
selanjutnya.
i.
Setelah sampai pada tiap-tiap titik tanda,
adakan pemeriksaan pada titik-titik tanda yang telah dilalui, supaya jangan
tersesat, dengan mengukur backazimuthnya. (sudut kompas semula + atau – 180
derajat) dengan kata lain backazimuth (BA) = sudut kompas ±180 derajat.
Beberapa hal yang benar-benar harus diperhatikan dalam menggunakan
kompas sebagi berikut:
1.
Hilangkan gangguan yang mempengaruhi kerja
kompas, terutama yang terbuat dari logam.
2.
Mengatur kedudukan kompas agar benar-benar
berada dalam posisi datar.
3.
Memproyeksikan tempat kedudukan kompas pada
titik awal pemberangkatan.
4.
Membidik titik sasaran, yaitu dengan membuat
celah pembidik, garis rambut dan obyek garis lintasan berada pada suatu garis
lurus.
5.
Membaca skala mendatar sudut kompas, yaitu
besarnya penyimpangan sudut antar kutub utara mangnet bumi dengan garis
lintasan.
4.
Sudut Kompas
Sudut kompas istilah
umumnya adalah azimuth, dihitung searah dengan putaran jarum jam. Beda sudut
peta karena acuan sudut kompas tidak dari utara peta tetapi dari utara magnetis
yang ditunjukkan oleh jarum kompas. Besarnya sudut kompas ialah besar derajat
yang diperoleh dari utara magnetik dengan garis lintasan.
5.
Tehnik Peta Kompas
Tehnik peta kompas
adalah upaya penggunaan gabungan dari peta dan kompas untuk membantu kita dalam
mempersiapkan alur perjalanan, mengetahui posisi kita atau sebuah titik atau
lokasi tetentu, untuk mengetahui apa saja yang ada dijalur yang akan kita
lewati dan masih banyak lagi aplikasi dan manfaat penggunaan dari penggabungan
peta dan kompas.
A.
Orientasi Peta atau
Orientasi Medan
Orientasi peta atau
orientasi medan adalah menyamakan kedudukkan peta dengan medan sebenarnya, atau
secara praktis adalah menyamakan arah utara peta dengan arah utara sebenarnya.
Untuk keperluan ini, kita perlu mengenal tanda-tanda medan yang ada di lokasi.
Misalnya saja dengan memastikan nama gunung, bukit, sungai ataupun tanda-tanda
alam lainnya yang terdapat pada peta. Atau dengan cara mengamati bentang alam
yang terlihat dan mencocokannya dengan gambar kontur yang ada dalam peta. Untuk
keperluan praktis, utara kompas (utara magnetik) dapat dianggap satu titik
dengan utara sebenarnya, tanpa memperhitungkan adanya deklinasi.
Secara terinci, langkah-langkah
untuk melakukan orientasi peta atau orientasi medan adalah sebagai berikut :
1.
Carilah tempat terbuka agar dapat melihat
tanda-tanda medan yang mencolok.
2.
Letakkan peta pada bidang yang datar.
3.
Samakan arah utara peta dengan arah utara
kompas, dengan jalan menggeser-geser petanya sehingga tepat dengan dengan
arah utara kompas, sesuaikan dengan bentang alam yang ada di hadapannya.
4.
Cari tanda-tanda alam yang paling menonjol di
sekeliling dan temukan atau cocokkan tanda-tanda tersebut dengan tanda-tanda
yang ada dalam peta. Lakukan juga untuk tanda-tanda medan lainnya.
5.
Ingat tanda-tanda medan itu, bentuknya dan
tempatnya di medan sebenarnya maupun di peta. Ingat hal-hal yang khas dari
setiap tanda-tanda medan.
B.
Azimuth dan BackAzimuth
Azimuth adalah sudut
antara satu titik dengan arah utara dari seorang pengamat. Azimuth disebut
juga sudut kompas. Bila kita berjalan dari satu titik ke titik lain dengan
sudut kompas tetap (potong kompas), maka harus diusahakan agar lintasan
perjalanan berupa satu garis lurus. Untuk itu digunakan tehnik BackAzimuth.
Prinsip BackAzimuth adalah
: membuat lintasan berada pada satu garis lurus dengan cara membidikan kompas
ke muka dan ke belakang jarak tertentu.
Dalam perjalanan agar
kita tidak tersesat atau menyimpang, patuhilah arah yang ditunjukan oleh sudut
kompas sesuai dengan arah yang akan dituju. Garis yang membentuk sudut kompas
tersebut adalah arah lintasan yang menghubungkan titik awal perjalanan dengan
titik akhir perjalanan. Banyak kasus yang menyebabkan kita tersesat adalah
kehilangan pedoman pada titik awal perjalanan. Ini dapat terjadi apabila kita
melakukan perjalanan yang sulit :
1.
Sulit untuk menemukan tanda-tanda alam yang
jelas sebagai titik awal, misalnya pada daerah rawa-rawa.
2.
Sulit untuk melakukan arah lintasan yang
lurus, misalnya penjelajahan lada hutan yang lebat.
3.
Sulit untuk melakukan orientasi atau pengenal
lapangan misal pada malam hari.
Untuk melakukan hal
tersebut dapat digunakan BackAzimuth. Jadi Backazimuth :
pembidikan balik dari Azimuth atau sudut kompas berpatokan
pada titik sasaran agar kita dapat mengoreksi arah lintasan.
Langkah-langkah BackAzimuth :
a.
Titik awal dan titik akhir perjalanan di
plotkan pada peta, kemudian tariklah garis lurus dan hitung sudut kompas yang
menjadi arah perjalanan. Hitung juga sudut dari titik akhir ke titik awal,
kebalikan arah perjalanan. Sudut kebalikan arah perjalanan ini adalah
sudut BackAzimuth.
b.
Perhatikan suatu objek yang menyolok (misalnya
pohon besar, pohon tumbang, longsoran tebing, susunan pohon yang khas, ujung
kampung dan sebagainya) pada titik awal perjalanan.
c.
Bidikan kompas sesuai dengan arah perjalanan kita
(sudut kompas), dan tandaidengan salah satu objek yang berada dijalur lintasan
yang akan dilalui pada arah itu.
d.
Setelah anda sampai pada objek itu, bidiklah
kompas kebelakang (BackAzimuth) untuk memeriksa kembali apakah anda
berada pada lintasan yang tepat. Bergeserlah ke kiri atau ke kanan untuk
mendapatkan BackAzimuth yang benar.
e.
Sering kali tidak ada objek yang dapat
dijadikan sasaran. Dalam hal ini pakailah teman kita sebagai titik objek
sementara dan dilakukan secara beranting. Lebih baik perjalanan lambat asal
tidak tersesat.
Keterangan :
SK – AB : Sudut kompas
perjalanan dari A ke B, SK – BC : Sudut kompas dari C ke B (BackAzimuth dari
C ke B), SK – BA : Sudut kompas dari B ke A (BackAzimuth dari B ke
A)
Cara mencari sudut
balik kompas atau sudut BackAzimuth:
1.
Bila sudut kompas sasaran kurang dari 1800,
maka BackAzimuthnya adalah : sudut kompas ditambah dengan 1800.
Contoh : Sudut kompas 450. Maka BackAzimuthnya adalah:
450+1800=2250.
2.
Bila sudut kompas sasaran lebih dari 1800,
maka BackAzimuthnya adalah : sudut kompas dikurangi dengan 1800.
Contoh : Sudut kompas sasaran lebih dari 2200. Maka BackAzimuthnya :
2200–1800=400.
Rumus mencari
sudut BackAzimuth:
Jika X0 < 1800 =
X0 + 1800
Jika X0 > 1800 =
X0 - 1800
C.
Resection atau ikatan
kebelakang
Prinsip resection adalah
menentukan posisi kita di peta dengan menggunakan dua atau lebih tanda medan
yang diketahui. Tehnik resection membutuhkan alam yang terbuka
untuk dapat membidik tanda medan. Tidak selalu seluruh tanda medan harus
dibidik. Jika kita sedang berada di tepi sungai, jalur sepanjang jalan atau
sepanjang suatu punggungan maka hanya perlu satu tanda medan lainnya yang
dibidik. Hal lainnya yang dapat membantu adalah penggunaan Altimeter (pengukur
ketinggian suatu tempat) namun akan dijelaskan dalam bagian tersendiri.
Langkah-langkah resection :
1.
Lakukanlah orientasi peta atau orientasi
medan.
2.
Cari tanda medan yang mudah dikenali di
lapangan dan di peta, sedikitnya dua buah. Tanda medan yang mudah dikenali :
jalan, sungai, tebing atau patahan, puncak gunung, dan lain-lain.
3.
Tandai kedudukkan dua titik atau lebih yang
sudah kita kenal berdasarkan keadaan medan atau peta.
4.
Bidiklah tanda-tanda medan tersebut dari
posisi kita dan catatlah sudut kompasnya.
5.
Pindahkan sudut bidikan yang didapat ke peta,
berilah titik pada tempat sudut hasil bidikan tersebut di atas peta.
6.
Tariklah garis lurus antara titik hasil
bidikan kompas di peta dengan titik yang kita bidik di peta.
7.
Buatlah dua buah garis lurus atau lebih hasil
bidikan dari kompas dari dua titik atau lebih yang diusahakan saling
berpotongan.
8.
Perpotongan garis tersebut adalah posisi kita
di peta.
Penjelasan
gambar resection di atas :
Kita sedang mencari
posisi kita di peta. Kita membidik puncak Gunung Arjuna dan puncak Gunung
Sindoro sebagai dua buah titik di medan yang telah kita ketahui. Hasil
pembidikan kita diperoleh :
1.
Untuk Gunung Arjuna diperoleh sudut 3150 DU
( dari utara) dan ditandai dengan titik A.
2.
Untuk Gunung Sindoro diperoleh sudut 350 DU
(dari utara) dan ditandai dengan titik B.
3.
Tariklah garis antara titik A dengan titik
puncak Gunung Arjuna. Demikian juga dengan titik B ditarik garis-garis dengan
titik puncak Gunung Sindoro.
4.
Perpotongan kedua garis tersebut, titik C
adalah posisi dimana kita berada di dalam peta.
D.
Intersection atau
ikatan kemuka
Prinsip intersection :
menentukan posisi suatu titik di peta dengan menggunakan dua titik atau lebih
tanda medan yang dikenali di lapangan. Intersection digunakan
untuk mengetahui posisi suatu benda atau posisi seseorang yang terlihat di
lapangan, tetapi sukar untuk dicapai. Pada intersection kita
sudah harus yakin posisi kita di peta.
Langkah-langkah intersection :
1.
Lakukan orientasi peta atau orientasi medan,
dan pastikan kedudukan kita di peta.
2.
Bidiklah obyek yang sedang kita amati, dari
posisi kita, yang telah kita ketahui di peta.
3.
Pindahkan sudut 1 yang kita dapati dari hasil
bidikan 1 itu ke atas peta berupa satu titik.
4.
Tariklah garis lurus yang menghubungkan titik
posisi kita di peta dengan titik hasil bidikan 1 itu.
5.
Bergeraklah ke posisi lain dan lakukanlah
kembali resection untuk memastikan kedudukkan kita di peta. Jarak
antara posisi 1 bidikan dengan posisi kita yang kedua diharapkan cukup
sebanding dengan sudut yang akan diambil/dibidik.
6.
Bidiklah obyek yang sedang kita amati, dari
posisi kita yang kedua.
7.
Pindahkan sudut kedua yang kita dapati dari
hasil bidikan kedua itu ke atas peta berupa satu titik.
8.
Tariklah garis lurus yang menghubungkan kedua
titik kedua posisi kita yang kedua dengan posisi titik hasil bidikan yang
kedua.
9.
Perpotongan antara kedua garis lurus tersebut
merupakan posisi obyek yang sedang kita amati di atas peta.
Biasanya posisi 1
maupun posisi kedua untuk melakukan bidikan adalah posisi yang tinggi, sehingga
dapat mengamati obyek yang berada di bawahnya.
Penjelasan
gambar intersection diatas :
Kita sedang mencari
sebuah titik C di atas peta.
1.
Posisi satu yang akan kita pakai untuk
membidik adalah puncak Semeru, karena kita sudah tahu kedudukannya di peta dan
mudah dipastikan di lapangan.
2.
Pembidikan dari puncak Semeru diperoleh sudut
bidikan terhadap objek kita ialah titik B. Titik B bersudut 450 DU
(dari utara).
3.
Kita berjalan lagi ke Puncak Bromo, dari
Puncak Bromo kita bidik lagi objek kita. Hasil bidikan yang kedua ditandai
dengan titik A. Titik A bersudut 3450 DU (dari utara).
4.
Tariklah garis lurus antara titik B dengan
puncak Semeru. Demikian juga tariklah garis lurus antara titik A dengan puncak
Bromo.
5.
Perpotongan kedua garis tersebut adalah titik
C, yaitu posisi objek kita di atas peta.
E.
Menentukan Arah Tanpa
Kompas
Dalam sebuah
perjalanan dapat saja secara mendadak kompas tidak berfungsi, macet, pecah,
atau rusak. Sebagai pengamanan biasakanlah membawa kompas cadangan yang
ditempatkan secara terpisah, atau jangan didekatkan. Misalnya saja ditempatkan
pada dua orang yang berbeda, sehingga tidak akan saling mempengaruhi medan
magnitnya.
Namun jika terpaksa
sekali, kita tidak dapat mempergunakan kompas karena gangguan-gangguan di atas
atau sama sekali tidak dapat berfungsi dan cadangan pun tidak ada, maka kita
terpaksa melakukan hal-hal yang cukup spektakuler untuk menentukan arah utara
dan selatan.
Berikut ini adalah beberapa cara menemukan
arah mata angin dengan bantuan :
1.
Tanda-tanda alam, misalnya:
a.
Kuburan islam menghadap ke utara.
b.
Mesjid menghadap kiblat, untuk wilayah
Indonesia mengarah ke sekitar barat laut.
c.
Bagian pohon yang berlumut tebal menunjukan
arah timur, karena pada pagi hari sinar matahari belum terik.
d.
Dengan jarum arloji
Untuk daerah sebelah
utara khatulistiwa, jarum kecil di arahkan ke matahari,garis pembagi sudut
antara jarum kecil dengan angka 12 (dua belas) akan menunjukan arah utara.
Untuk daerah sebelah selatan khatulistiwa, caranya sama, hanya saja yang
didapatkan arah selatan.
e.
Dengan perbintangan
Beberapa macam rasi
bintang yang dapat dijadikan alat bantu untuk menentukan arah utara dan
selatan:
1.
Rasi bintang crux (bintang
salib/gubuk penceng)
Rasi bintang ini
terdiri dari empat bintang utama dan satu bintang bantu. Empat bintang utama
membentuk layang-layang. Untuk mengetahui arah utaranya, perhatikan arah yang
ditunjukan oleh posisi tiga buah bintang utama yang terdekat. Sedangkan satu
utama yang terjauh menunjukan selatan.
2.
Rasi bintang orion
Bintang orion adalah
suatu gugusan bintang yang menyerupai gambar orang yang sedang membawa pedang
dan ikat pinggang. Tiga buah bintang di atas membentuk “kepala”, yang
menunjukan arah utara. Dan arah yang ditunjukan “pedang” adalah menunjuk arah
selatan.
3.
Rasi bintang waluku (bajak)
dan bintang kutub
Bintang waluku adalah
sebuah gugusan bintang yang mudah ditemukan. Bentuknya mirip centong. Bintang
ini sebenarnya merupakan bagian dari gugusan bintang Ursa Mayor (beruang
besar) dimana fungsi bintang ini menunjukan bintang kutub atau utara yang
terdapat pada rangkaian bintang kutub atau beruang kecil (Ursa Minor).
Keistimeawan bintang ini, sekalipun gugusan bintang lainnya berputar di langit
pada malam hari, tetapi bintang kutub tetap berada di utara.
VI.
ANALISIS PERJALANAN
Analisa pejalanan perlu
dilakukan agar kita dapat lebih membayangkan kira-kira alur lintasan perjalanan
yang akan kita lalui. Analisa perjalanan dilakukan sebelum perjalanan dimulai,
yaitu dengan jalan mempelajari peta yang akan digunakan.
Yang perlu dianalisa dengan
cermat adalah jarak yang akan ditempuh, waktu yang akan dipergunakan dan
tanda-tanda medan.
a.
Jarak yang akan ditempuh
Jarak diperkirakan
dengan mempelajari peta perjalanan. Yang perlu diperhatikan adalah jarak
sebenarnyadan yang akan kita tempuh, bukan jarak horizontal. Kita dapat
memperkirakan jarak (kondisi medan) lintasan yang akan ditempuh dengan jalan
memproyeksikan lintasan (lihat gambar garis kontur) kmudian mengalihkannya
dengan skala untuk memperoleh jarak sebenarnya.
b.
Waktu yang akan dipergunakan
Ada teori klasik untuk
memperkirakan waktu tempuh ini, yaitu aturan Naismith, yaitu kecepatan
rata-rata orang berjalan pada medan horizontal (datar) adalah 5 km/jam dan
setiap kenaikan 300 m ditambah 0,5 jam.
Contoh : jika
direncanakan perjalanan sejauh 10 km dengan pertambahan kenaikan vertikal 600
m, maka waktu tempuh kita adalah :
(10 km/5 km/jam) +
(600 m/300 m) x (0,5 jam) = 3 jam
untuk kecepatan
perjalanan pada medan yang menurun digunakan rumus : setiap penurunan 300 m,
waktu tempuhnya 5 km/jam + 10 menit.
Catatan : perhitungan tersebut
hanya berlaku pada medan yang tidak bersemak. Selain itu waktu tempuh akan
bervariasi tergantung pada hal-hal seperti keadaan fisik, beban yang dibawa,
keadaan lintasan ( berpasir, tanah keras, berlumpur,bersalju) dan kondisi
cuaca.
c.
Tanda-tanda medan
Cari dan
ingat-ingatlah tanda-tanda medan yang ada di peta yang mungkin dapat menjadi
pedoman dalam menempuh perjalanan. Misalnya sungai, danau, tebing dan
lain-lain.
d.
jenis-jenis medan :
hill walking =
perjalanan mendaki bukit-bukit atau pegunungan yang belum membutuhkan peralatan
khusus dan teknik khusus.
climbing = pendakian
yang membutuhkan alat dan teknis khusus, climbing dibagi menjadi 2 macam yaitu
:
1.
rock climbing = pendakian pada batu yang
membutuhkan alat dan teknik khusus
2.
snow ice climbing = pendakian pada gunung es
atau daerah bersalju yangmembutuhkan alat dan teknik khusus
scrambling = pendakian
pada tebing-tebing batu yang tidak terlalu terjal yang terkadang menggunakan
tangan untuk keseimbangan. Bagi pemula biasanya dipasang tali untuk pengaman
jalur untuk lintasan
e.
Medan tidak sesuai Peta
Jangan terlalu cepat
membuat kesimpulan untuk menyalahkan petanya.
Memang banyak
sungai-sungai kecil yang tidak tergambar di peta, karena sungai tersebut
mengering ketika musim panas. Ada kampung yang sudah berubah, jalan setapak
yang hilang dan masih banyak perubahan-perubahan lainnya yang mungkin terjadi.
Bila tidak ada
kesesuaian antara peta dengan kondisi lapangan, baca kembali peta tersebut
dengan lebih teliti. Cari tanda-tanda medan yang mudah dikenali. Jangan terpaku
pada satu gejala saja yang ada di peta, sehingga hal-hal lain yang dapat
dianalisa terlupakan. Kalau terlalu banyak hal, yang tidak sesuai dengan peta
kemungkinan besar kita yang salah, salah mengikuti punggungan, salah menyusuri
sungai, atau salah dalam melakukan resection. Peta topografi 1:25000 atau
1:50000 umumnya cukup teliti.
VII. ALTIMETER
Altimeter merupakan
alat pengukur ketinggian yang bisa membantu dalam menentukan posisi. Pada medan
yang bergunung tinggi, resection dengan menggunakan kompas sering tidak banyak
membantu, disini altimeter lebih bermanfaat. Dengan menyusuri
punggungan-punggungan yang muda dikenali di peta, altimeter akan lebih berperan
dalam perjalanan, yang harus diperhatikan dalam pemakaian altimeter :
a.
Setiap altimeter yang dipakai harus
dikalibrasi, dengan cara diperiksa ketelitian altimeter di titik-titik
ketinggian yang pasti. Contohnya di tepi laut atau stasiun kereta api.
b.
Altimeter sangat peka terhadap guncangan, perubahan
cuaca, dan perubahan temperatur
VIII. PROTRACTOR
Protractor adalah alat yang berbentuk persegi empat yang
digunakan untuk mempermudah kita menentukan koordinat dan sudut pada peta.
Biasanya 1 buah pratractor memiliki 3 skala yang berbeda, namun tidak dapat
digunakan untuk membaca koordinat geografis yang didalamnya terdapat :
a.
Pembagian derajat
b.
Prmbagian peribuan
c.
Skala koordinat 1 : 100.000 1 : 50.000 1 :
25.000
d.
Titik pusat untuk pembagian derajat dan titik
silang pada tengah – tengah protractor
e.
Tanda indeks dan untuk skala koordinat adalah
sisi tegak dan siku –siku segi tiga
Protractor dapat
dipergunakan untuk :
1.
Menentukan sudut peta
2.
Plotting sudut peta
3.
Plotting koordinat
4.
Menentukan
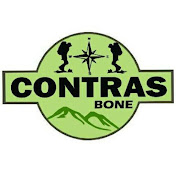









Komentar
Posting Komentar